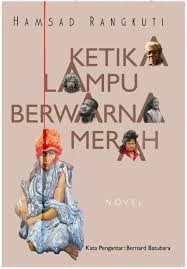
Judul : Ketika Lampu Berwarna Merah
Penulis : Hamsad Rangkuti
Jumlah halaman : 228 hlm
Penerbit : DIVA Press
Cetakan : I, Mei 2016
ISBN : 978-602-391-148-6
Genre: Fiksi Sosial, Fiksi Lokal
Rating: 3/5
Jika engkau ingin melihat kaum ibu dengan gendongan balita dekil, lampu merah tempatnya. Kalau engkau hendak melihat kaum bapak berkaki pengkor atau bertangan sebelah, lampu merah juga tempatnya. Ingin melirik anak-anak mengamen dan menengadah tangan? Lampu merahlah tempatnya.
Jangan engkau tanya seperti apa aroma tubuh dan tampilan mereka. Mungkin cukup untuk membuat para penumpang menahan nafas atau mengernyitkan dahi. Di satu sisi, lampu merah membuat dongkol para supir dan majikan yang ingin segera berleha di rumah mereka. Di sisi lain, persimpangan dan lampu merah menjadi panggung senyum bagi kaum gepeng mengais rezeki. Ironis memang.
Tak sekali dua barangkali kita berjumpa dengan kaum gepeng ketika lampu lalu lintas berganti merah. Mulai dari yang berpura-pura pengkor sampai yang benar-benar pengkor, pun para pengamen yang bersuara bak Iwa K hingga yang cempreng menyakitkan telinga, seolah kita melihat babak demi babak drama negeri ini dari balik layar kaca mobil pribadi atau angkutan umum.
Tapi, yah … hanya sebatas ketika lampu merah menyala. Setelah itu? Para pengemudi dan penumpang tentunya akan melanjutkan kembali pikiran mereka ke tempat lain, meninggalkan gembel dan pengemis yang entah bagaimana kelanjutan hidup mereka setelah lampu berwarna hijau.
Sudah bukan rahasia lagi sebenarnya bagaimana kehidupan kaum gepeng di negeri ini. Hampir dari kita semua tahu bahwa hidup mereka jauh dari kata layak. Sekedar bisa memenuhi kebutuhan perut yang sejengkal itu saja mungkin sudah lebih dari cukup.
Hendak bermimpi bersekolah tinggi atau bercita-cita memiliki ini itu? Yah, barangkali itu hanya menjadi sebatas mimpi. Hidup di lingkungan masyarakat pinggiran dan terbuang tak akan pernah terbayangkan oleh sebagian orang.
Kehidupan di mana anak kecil dipaksa mencari uang untuk memberi makan entah siapa. Kehidupan di mana anak-anak perempuan harus berjuang melepaskan cengkeraman dan tatapan buas lelaki hidung belang beraroma bir. Lingkungan di mana para wanita tuna susila hidup menjajakan diri demi selembar dua puluh ribu rupiah. Ya Tuhan … tak terbayangkan betapa ngerinya.
Tapi, Hamsad Rangkuti berhasil menampilkan babak-babak kehidupan kaum pinggiran di atas seolah nyata melalui novel Ketika Lampu Berwarna Merah.
Adalah Kartijo yang ditinggalkan anak lelakinya, Basri, yang minggat dari rumah demi melihat Monas di Jakarta. Kartijo dan istrinya, Surtini, beserta orang-orang sekampung terpaksa harus pindah ke Sumatera mengikuti program transmigrasi, meninggalkan tanah kelahiran mereka di Wonogiri karena desanya akan dijadikan waduk. Hanya satu keinginan Surtini; menemukan anaknya.
Jadilah Kartijo, dengan waktu yang sangat mepet, mencari Basri ke Jakarta dan berjanji akan mengejar kapal yang akan mereka tumpangi ke Sumatera di Tanjung Priok. Sementara ayahnya sibuk mencari, sang anak ternyata harus bergulat dengan kehidupan Ibu Kota yang keras dan berbahaya bersama teman-temannya.
Lewat Basri, Pipin si kaki pengkor yang ditinggal mati ibu bapaknya, Bustami si pemabuk, Sanip si tukang mayat, serta tokoh-tokoh lainnya dengan karakter yang cukup kuat, narasi Hamsad Rangkuti mampu menggiring degup jantung kita berdetak agak cepat merasakan ketegangan konflik para tokohnya.
Membuat kita bertanya-tanya bagaimana akhir dari kisah kaum pinggiran ini. Rasanya hampir seperti gambaran realita negeri ini. Katanya di negeri ini, orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Nyatanya, bagai pungguk merindukan bulan. Dengan realita yang ada di sekitar kita, Ketika Lampu Berwarna Merah seakan-akan menjadi sebuah sindiran bagi kita dan negeri ini, bahwa gepeng dan kaum terpinggirkan lainnya membutuhkan campur tangan pihak lain untuk membuka jalan yang lebih baik, membuka lembaran baru bagi mereka.
Tanpa menceramahi, tanpa menggurui, Hamsad Rangkuti menawarkan makna tersirat lewat narasinya. Menurut saya ini menjadi salah satu kelebihan dari karyanya. Selain itu, Ketika Lampu Berwarna Merah dituturkan dengan penggambaran yang sangat detail sehingga saya cukup menikmati deskripsi-deskripsi di dalamnya tanpa terasa membosankan.
Selain gambaran realita kaum yang terpinggirkan, Hamsad Rangkuti juga menunjukkan bahwa sepahit-pahitnya kehidupan yang dijalani, siapapun memiliki mimpi yang ingin diwujudkan, meski bagi orang lain mimpi itu terdengar sangat sederhana. Entah dengan cara apa, kaum gepeng tentu saja ingin mengubah nasibnya.
Semangat itulah yang barangkali terus membawa mereka bergerak mengejar harapan dengan kaleng-kaleng mentega dan krecekan di tangan mereka, menyongsong lampu berwarna merah. Sekali lagi, sebungkus nasi sudah menunggu mereka di perempatan itu.
Wajah-wajah pias berbalut dekil
Berselimut debu
Sesuap demi sesuap
Nasi tanpa apa
Pada balutan tulang
Di rangkulan angin malam
Laparnya tak kau rasa
Dahaga pun tak terpuaskan
Entah ….
Sinismu terpancang
Jijik, angkuh
Katamu, mereka sampah
Atau kitakah?
(Balada Orang Pinggiran – Evyta AR)